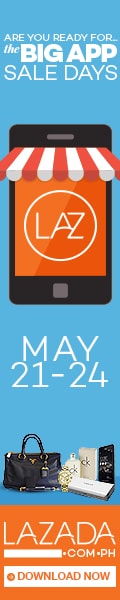Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim

JAKARTA PUSAT (Beritakeadilan.com, DKI Jakarta)-Tepat pada 2 Januari 2026, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidananya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada 17 Desember 2025 yang akan resmi berlaku berdampingan dengan KUHP Nasional, Undang Undang nomor 1 Tahun 2023. Setelah lebih dari empat dekade, KUHAP warisan 1981 yang menggantikan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) kolonial akhirnya mengalami pembaruan menyeluruh. Ini adalah momentum bersejarah yang tidak boleh disia-siakan.
Siapkah para hakim kita?
Bukan sekadar soal menghafal pasal-pasal baru. Yang lebih fundamental adalah mempersiapkan kerangka berpikir, nalar yuridis yang adaptif terhadap perubahan paradigma pembuktian. Sebab, jantung peradilan pidana terletak pada pembuktian. Di situlah nasib seseorang ditentukan: bersalah atau bebas. Setiap perubahan dalam sistem pembuktian akan berdampak langsung pada cara hakim menilai bukti dan menjatuhkan putusan.
Perluasan Alat Bukti yang Signifikan
KUHAP lama mengenal lima alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1): keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. KUHAP baru melalui Pasal 235 ayat (1) memperluasnya menjadi delapan jenis dengan penambahan yang sangat signifikan: barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.
Perubahan paling mencolok adalah penggantian "petunjuk" dengan "pengamatan hakim". Wakil Menteri Hukum Prof. Edward O.S. Hiariej menegaskan bahwa tidak ada negara mana pun di dunia yang menjadikan "petunjuk" sebagai alat bukti. Istilah ini dianggap sebagai kekeliruan penerjemahan dalam pembahasan KUHAP 1981. Pada KUHAP baru alat bukti” Petunjuk” diubah menjadi, ”pengamatan hakim“ yang dikenal dalam praktik hukum internasional, khususnya sistem common law, sebagai judge's own observation.
Perbedaannya bukan sekadar semantik, melainkan substansial. "Petunjuk" dalam KUHAP lama bersifat luas dan bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, termasuk hal-hal yang terjadi di luar sidang. Sementara "pengamatan hakim" terbatas pada apa yang diamati langsung di persidangan. Bagaimana saksi memberikan keterangan, bagaimana mimik dan gestur terdakwa saat merespons pertanyaan, bagaimana barang bukti didemonstrasikan, serta keadaan-keadaan yang mengelilingi fakta persidangan. Ini menegaskan prinsip unmiddelbarkeit, pendekatan langsung dalam hukum acara pidana modern.
Selain itu, barang bukti (corpus delicti) kini diakui sebagai alat bukti mandiri. Dalam KUHAP lama, barang bukti hanya dipandang sebagai objek pendukung yang harus dihubungkan dengan alat bukti lain. KUHAP baru mengangkat statusnya menjadi alat bukti yang otonom. Meskipun demikian, hakim tetap harus memahami bahwa barang bukti adalah "saksi bisu" (stille getuige) yang memerlukan penjelasan melalui keterangan saksi atau ahli untuk menghubungkannya dengan tindak pidana yang didakwakan.
Bukti elektronik juga mendapat kedudukan tegas sebagai instrumen pembuktian independent, mengakhiri perdebatan panjang apakah ia termasuk alat bukti tersendiri atau sekadar petunjuk. Ketentuan ini menjawab kebutuhan zaman di mana kejahatan semakin banyak meninggalkan jejak digital, seperti rekaman CCTV, data transaksi elektronik, pesan aplikasi, hingga metadata dokumen digital.
Yang paling fleksibel sekaligus menantang adalah penambahan "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian". Ketentuan ini memberi ruang bagi hakim untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dan teknologi di masa depan yang belum terbayangkan saat ini. Namun, tanpa definisi dan kriteria yang jelas, ia berpotensi ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap hakim. Di sinilah pentingnya pedoman teknis dari Mahkamah Agung.
Pergeseran Paradigma
Secara formal, KUHAP baru melalui Pasal 230 masih menganut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie): hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dua unsur ini bersifat kumulatif tidak boleh salah satu saja. Ada alat bukti tetapi tidak ada keyakinan, tidak dapat menjatuhkan pidana. Sebaliknya, ada keyakinan tetapi tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah, juga tidak dapat memidana.
Namun, dengan perluasan jenis alat bukti dan keleluasaan menggunakan "segala sesuatu" untuk pembuktian, terjadi pergeseran paradigma ke arah conviction raisonnée keyakinan rasional. Dalam sistem ini, hakim memiliki ruang lebih luas untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai bukti, tetapi dengan konsekuensi yang tidak ringan: setiap keyakinan harus dilandasi pertimbangan yang memadai, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Di sinilah letak taruhannya. Pasal 235 KUHAP baru menegaskan bahwa pertimbangan yang tidak memadai (onvoldoende gemotiveerd) merupakan salah satu alasan pembatalan putusan demi hukum. Keleluasaan yang diberikan undang-undang berbanding lurus dengan beban pertanggungjawaban. Hakim tidak bisa lagi sekadar menyatakan "berdasarkan keyakinan" tanpa menguraikan secara komprehensif bagaimana keyakinan itu terbentuk dari fakta-fakta persidangan.
Dalam konteks praktis, pergeseran ini menuntut hakim untuk lebih cermat dalam menyusun pertimbangan hukum. Setiap alat bukti yang digunakan harus dijelaskan relevansinya dengan dakwaan, bagaimana ia diperoleh, bagaimana keabsahannya, dan seberapa kuat nilai pembuktiannya. Pertimbangan yang dangkal akan menjadi titik lemah yang mudah diserang di tingkat banding atau kasasi.
Lima Kerangka Berpikir untuk Implementasi
Menghadapi perubahan fundamental ini, hakim perlu mempersiapkan setidaknya lima kerangka berpikir baru yang akan menjadi panduan dalam mengimplementasikan ketentuan KUHAP baru.
Pertama, penguatan prinsip legal scrutiny. Hakim bukan lagi sekadar "mulut undang-undang" (la bouche de la loi) yang pasif menunggu bukti disodorkan, melainkan pemeriksa aktif yang melakukan pengamatan cermat terhadap seluruh proses persidangan. Setiap gerak-gerik saksi dan terdakwa, setiap intonasi dalam memberikan keterangan, setiap kontradiksi dan konsistensi jawaban, harus tercatat dalam memori yuridis hakim dan menjadi bahan pertimbangan. Dalam implementasinya, hakim perlu membiasakan diri untuk membuat catatan persidangan yang lebih detail bukan hanya mencatat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana hal itu dikatakan dan dalam konteks apa.
Kedua, pengamatan yang terverifikasi dan akuntabel. Pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak boleh menjadi pintu masuk subjektivitas berlebihan yang dapat menggeser prinsip pembuktian objektif. Pengamatan harus tetap berbasis pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi, bukan pada prasangka, stereotip, atau asumsi personal hakim. Dalam praktik, hakim harus mampu mengartikulasikan dengan jelas dalam putusan: "Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, terlihat bahwa..." diikuti dengan deskripsi faktual yang spesifik dan relevan. Keadilan harus tetap dapat diverifikasi oleh siapa pun yang membaca putusan, bukan sekadar diyakini oleh hakim yang memutus.
Ketiga, penguasaan bukti elektronik dan digital forensic. Era digital menuntut hakim memahami konsep-konsep dasar yang krusial dalam penanganan bukti elektronik. Hakim perlu memahami chain of custody rangkaian prosedur yang memastikan bukti elektronik tidak mengalami perubahan atau manipulasi sejak ditemukan hingga dihadirkan di persidangan. Hakim juga perlu memahami standar autentikasi digital untuk menilai apakah bukti elektronik yang diajukan adalah asli dan tidak dimanipulasi. Dalam implementasinya, hakim harus kritis mempertanyakan: siapa yang pertama kali menemukan bukti elektronik ini? Bagaimana proses pengambilannya? Dengan alat apa? Siapa saja yang menyentuh atau mengakses bukti ini? Apakah ada jaminan integritas data? Tanpa pemahaman ini, hakim akan kesulitan menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti berbasis teknologi.
Keempat, kewajiban pertimbangan yang komprehensif dan memadai. Setiap penggunaan alat bukti termasuk alat bukti fleksibel berupa "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian" harus disertai penjelasan mengenai tiga aspek: relevansinya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, keabsahan cara memperolehnya, dan nilai kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan alat bukti lain. Putusan yang miskin pertimbangan akan mudah dibatalkan di tingkat banding atau kasasi dengan alasan onvoldoende gemotiveerd.
Dalam praktik, hakim perlu membiasakan pola pikir: "Untuk setiap alat bukti yang saya gunakan, apakah saya sudah menjelaskan mengapa bukti ini relevan, bagaimana bukti ini diperoleh secara sah, dan seberapa kuat bukti ini membuktikan dakwaan?"
Kelima, konsistensi terhadap asas praduga tak bersalah. Perluasan alat bukti dan keleluasaan hakim tidak boleh mengerosi prinsip fundamental presumption of innocence. Pengamatan hakim harus digunakan secara berimbang tidak hanya untuk memperkuat keyakinan tentang kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk menangkap hal-hal yang meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa. Dalam keraguan yang beralasan, terdakwa harus diuntungkan (in dubio pro reo). Hakim harus ingat bahwa tujuan peradilan pidana bukan sekadar menghukum, melainkan mencari kebenaran materiil dan menegakkan keadilan.
Mekanisme Pengakuan Bersalah: Peran Baru Hakim
KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam Pasal 78 yang mengubah dinamika pembuktian secara signifikan. Melalui mekanisme ini, terdakwa dapat mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif, yang membuka peluang perubahan jenis acara dari pemeriksaan biasa menjadi pemeriksaan singkat. Ini berbeda dengan KUHAP lama yang sama sekali tidak mengenal perubahan jenis acara setelah persidangan dimulai.
Dalam kerangka pembuktian, ketika pengakuan bersalah terjadi, dasar pembuktian berubah secara fundamental. Dalam acara biasa, terdapat kewajiban pembuktian penuh (full evidentiary hearing) yang mencakup pemanggilan saksi fakta, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan barang bukti secara detail. Namun, ketika hakim menerima pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela dan didukung bukti permulaan yang cukup, kompleksitas pembuktian dapat disederhanakan.
Namun, peran hakim justru semakin krusial dalam mekanisme ini. Hakim harus memastikan bahwa setiap pengakuan bersalah diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan atau paksaan dalam bentuk apa pun. Pasal 205 ayat (2) KUHAP baru mengatur serangkaian pertanyaan yang harus diajukan hakim untuk memverifikasi kesadaran dan kesukarelaan pengakuan mirip dengan praktik. Boykin colloquy di Amerika Serikat. Hakim juga harus memastikan bahwa pengakuan didukung oleh bukti permulaan yang memadai pengakuan semata tanpa dukungan bukti lain tidak cukup untuk menjatuhkan pidana.
Waktunya Bersiap
Momentum transformasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman teknis implementasi. Diperlukan panduan yang jelas mengenai standar penilaian bukti elektronik, batasan penggunaan pengamatan hakim, kriteria "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian", serta prosedur verifikasi pengakuan bersalah.
Program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh hakim menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. Pelatihan tidak cukup hanya bersifat sosialisasi normatif, tetapi harus mencakup aspek-aspek teknis: pelatihan digital forensic dasar agar hakim memahami prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik, pelatihan metode observasi berbasis psikologi hukum agar pengamatan hakim menjadi lebih sistematis dan terstruktur, serta simulasi persidangan dengan skenario KUHAP baru agar hakim terbiasa dengan dinamika acara yang berubah.
Pengawasan oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga perlu diperkuat. Dengan keleluasaan yang lebih besar yang diberikan kepada hakim, potensi penyalahgunaan juga meningkat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak mereduksi asas praduga tak bersalah, bahwa pertimbangan hukum memenuhi standar kelayakan, dan bahwa keseluruhan proses peradilan berjalan sesuai koridor yang ditetapkan.
Perubahan hukum acara bukan sekadar perubahan prosedur administratif. Ia adalah perubahan cara berpikir, cara menilai, dan cara memutus. Hakim yang tidak mempersiapkan diri akan tertinggal dan yang menanggung akibatnya adalah masyarakat pencari keadilan. Putusan yang tidak memenuhi standar pertimbangan yang memadai akan dibatalkan, yang berarti penundaan keadilan bagi para pihak. Lebih buruk lagi, kesalahan dalam menilai bukti dapat berakibat fatal: orang yang tidak bersalah dihukum, atau pelaku kejahatan lolos dari pertanggungjawaban.
Tanggal 2 Januari 2026 bukan lagi masa depan yang jauh. Ia sudah di depan mata, tinggal menghitung hari. Waktu untuk bersiap adalah sekarang bukan besok, bukan minggu depan, tetapi sekarang. Setiap hakim memiliki tanggung jawab personal untuk mempelajari KUHAP baru secara mendalam, memahami perubahan-perubahan fundamentalnya, dan menyesuaikan kerangka berpikirnya. Institusi peradilan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses pembelajaran ini.
Dengan persiapan yang matang, KUHAP baru akan menjadi instrumen yang membawa peradilan pidana Indonesia ke tingkat yang lebih modern, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan. Tanpa persiapan, ia hanya akan menjadi teks undang-undang yang gagal dalam implementasi. Pilihan ada di tangan kita semua terutama para hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di ruang sidang
M.NUR